The Doors: Musik Saat Pintu Gelap Dibuka Pelan-Pelan

The Doors: Musik Saat Pintu Gelap Dibuka Pelan-Pelan
Malam itu, hujan turun tipis di Jakarta. Saya duduk di taksi online, lampu-lampu kota memantul di kaca jendela. Sopirnya memutar playlist acak dari ponsel, lalu tiba-tiba masuk suara hujan buatan, denting keyboard, dan bisikan pelan: “Riders on the storm…”
Dalam sekejap, jalan Sudirman berubah jadi jalan kosong di Los Angeles awal 70-an. Itulah kekuatan The Doors: mereka tidak sekadar bikin lagu, mereka mengubah ruangan tempat kita duduk.
The Doors lahir di LA: Jim Morrison, penyair mabuk yang kebetulan tampan, Ray Manzarek dengan organ yang terdengar seperti gereja yang diserang mimpi buruk, Robby Krieger dengan gitar melengkung, dan John Densmore, drummer yang lebih dekat ke jazz daripada rock biasa. Tidak ada bass tetap, tidak ada gimmick besar. Hanya empat orang, satu pintu, dan imajinasi yang berlebihan.
Di tengah kultur flower power yang cerah dan penuh bunga, The Doors memilih jalur lain: gelap, erotik, filosofis, kadang menakutkan. “Break On Through (To the Other Side)” terdengar seperti undangan sekaligus peringatan. Jim tidak sekadar menyanyi, dia memanggil.
Seorang teman saya, DJ radio di Surabaya, pernah bilang:
“Kalau Beatles itu pagi hari, The Doors itu jam 2 dini hari. Lo dengerin sendirian, lampu redup, dan tiba-tiba ngerasa ditemani, tapi bukan oleh hal yang sepenuhnya nyaman.”
Yang membuat The Doors unik adalah keseimbangan antara puisi dan bahaya. “The End” misalnya, bisa terdengar seperti doa, bisa juga seperti mimpi buruk paling jujur yang pernah direkam. Morrison menyanyikan lirik-lirik yang, di atas kertas, lebih dekat ke buku sastra daripada booklet album rock.
Ray Manzarek pernah bilang musik mereka seperti “cinema for your ears”. Di “Light My Fire”, solo organ dan gitar itu terasa seperti kamera yang bergerak bebas di kepala kita. Tidak heran, sampai sekarang masih jadi lagu wajib di kafe-kafe lama dan bar yang menolak menyerah pada TikTok hits.
Seorang barista di Yogyakarta tertawa waktu saya tanya kenapa dia selalu mutar The Doors sore hari:
“Lagunya bikin kafe kerasa punya rahasia. Orang yang tau The Doors biasanya langsung senyum kecil. Kayak kode rahasia antar anggota sekte.”
Generasi muda menemukan mereka dengan cara lain. Lewat film, serial, YouTube, sampai FYP random. Di kolom komentar live “Touch Me” ada yang menulis:
“Gue lahir tahun 2004, tapi berasa salah tahun. Harusnya gue nongkrong di klub kecil tahun 1969 nonton band ini.”
Yang menarik, The Doors jarang terdengar “jadul”. Produksi mereka memang 60-an, tapi suasana yang mereka ciptakan—kesepian, keinginan kabur, rasa hampa di tengah keramaian—terasa sangat 2020-an.
Seorang mahasiswa psikologi di Bandung bilang pada saya:
“‘People Are Strange’ itu kayak soundtrack resmi generasi yang tumbuh dengan media sosial. Lo bisa punya ribuan teman, tapi tetap ngerasa jadi orang aneh di kerumunan.”
Tentu, sulit bicara The Doors tanpa menyentuh mitos terbesar mereka: Jim Morrison. Dia bukan hanya frontman; dia tokoh utama sebuah film panjang yang berakhir terlalu cepat di Paris, umur 27. Tubuhnya berhenti, tapi karakter “Lizard King” yang ia ciptakan terus berkeliaran di poster kamar, kaos vintage, dan avatar media sosial.
Namun kalau kita kupas mitosnya, yang tersisa tetap musik. The Doors bukan sekadar kultus Jim Morrison; mereka adalah dialog empat orang tentang apa yang bisa dilakukan rock jika dibiarkan liar. Densmore menahan lagu agar tidak jatuh berantakan, Krieger membawa unsur flamenco dan blues, Manzarek menyediakan ruang mimpi, Morrison menyalakan api.
Sebagai jurnalis musik, saya selalu merasa The Doors adalah bukti bahwa rock tidak harus selalu soal volume. Dengarkan “Crystal Ship” atau “Indian Summer”. Pelan, nyaris berbisik. Tapi justru di situ ketegangan terbaik mereka muncul. Seperti dua orang yang saling menatap terlalu lama, tahu ini berbahaya, tapi tidak mau mengalihkan pandangan.
Di era sekarang, ketika banyak lagu dirancang agar “aman” di playlist kantor dan mal, The Doors terdengar seperti tamu yang tidak diundang tapi tidak bisa diusir. Mereka membawa kata-kata tentang kematian, seks, pemberontakan, dan kegagalan mencari makna—hal-hal yang diam-diam tetap kita pikirkan saat memandangi plafon kamar jam tiga pagi.
Seorang pengemudi ojek online yang saya temui malam itu akhirnya bertanya,
“Mas, ini band apaan? Kok kayak bikin gue pengin ngebut tapi sekaligus mikir hidup?”
Saya tertawa.
“The Doors,” jawab saya. “Band yang bukain pintu ke sisi kepala yang biasanya kita kunci rapat-rapat.”
Dan mungkin, selama masih ada orang yang berani memutar “Riders on the Storm” saat hujan, atau “The End” saat sendirian, pintu itu tidak akan pernah benar-benar tertutup.
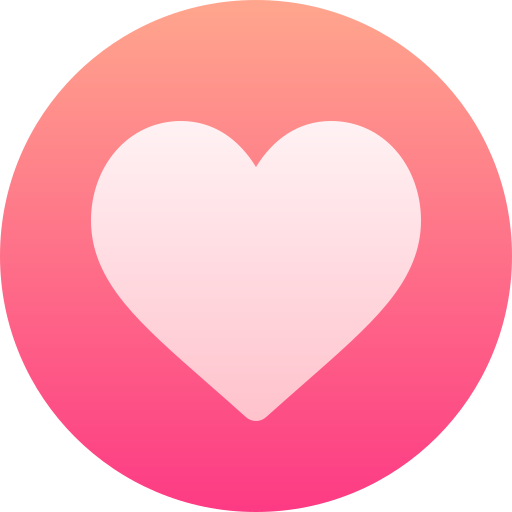
- Art
- Causes
- Crafts
- Dance
- Drinks
- Film
- Fitness
- Food
- Toys & Games
- Gardening
- Health
- Início
- Literature
- Music
- Networking
- Outro
- Party
- Religion
- Shopping
- Sports
- Theater
- Wellness



